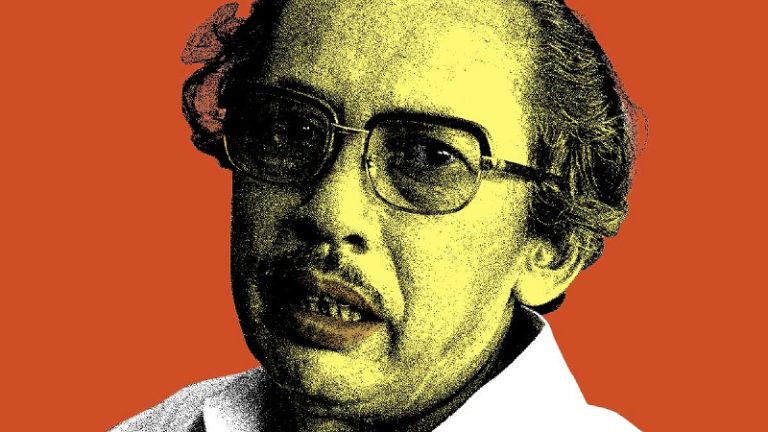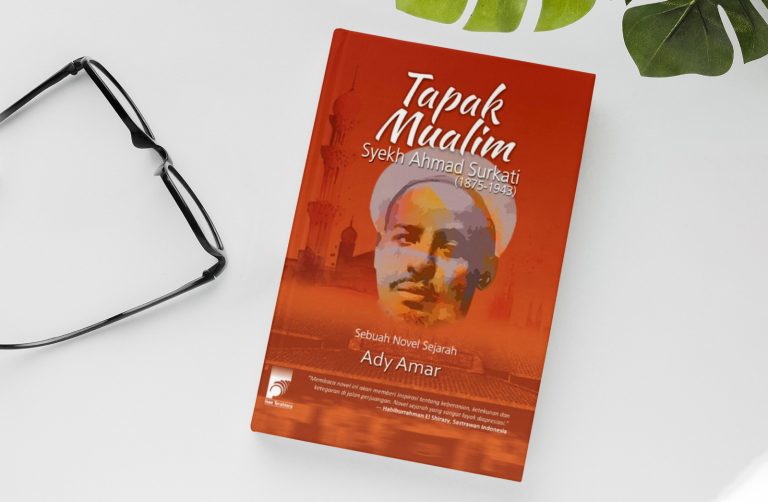Ira semakin teriris. Suara alam tidak bisa meraja di perasaannya. Tiba-tiba ibunya menyuruh membawa garam dan gelas. Ira pun meleparkan garam ke danau.
Cerpen oleh Kirana Aura Zahy, siswa kelas IX SMA Muhammadiyah 10 (Smamio) GKB Gresik Jawa Timur
Tagar.co – Angin berbisik lembut menembus telinga Lembahira. Kicau burung kecil bersahut menginspirasi aurora pemandangan sekitar pedesaan.
Lembahira atau yang akrab disapa Ira. Penulis muda yang menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian dan kegagalan. Setiap hari, dia duduk di bawah pohon jati yang rindang di halaman rumah.
Menggoreskan kata demi kata di atas kertas, membiarkan imajinasinya melambung jauh melewati batas.
Namun, setiap kali mengirimkan tulisan ke penerbit, dia hanya menerima surat penolakan yang dingin. Penolakan yang seakan-akan menjadi peluru yang menghancurkan harapan yang dia bangun dengan penuh cinta.
Rasa putus asa seringkali menggerogoti impiannya. Asa yang mempertanyakan bakatnya dan arti dari setiap goresan yang dibuat. “Kejam,” gumamnya dalam hati yang membuat kedua matanya mengembun.
Di tengah kebisingan pikiran, Ira menemukan kenyamanan dalam ritualnya. Dia mulai menjadikan suara alam sebagai teman menulisnya.
Baca juga: Laut dan Cerita di Temi Sore Itu
Irama gemericik air sungai yang mengalir dekat, suara angin membisikkan rahasia, dan kicauan burung yang seolah memberi semangat. Suara alam benar-benar menggumpal dan membumbung dalam aura angannya.
Meskipun tantangan terus berdatangan, tangan Ira tak pernah berhenti menulis.
“Ira, kenapa kamu melamun, ngga dilanjutin menulisnya? Apa ada yang mengganggu pikiranmu?” tanya Ibu, memecah lamunan Ira lembut.
“Ah.. tidak apa-apa, Bu,” jawab Ira dengan wajah datar.
“Bohong, naluri seorang Ibu itu tidak pernah salah, Nduk,” ucap Ibu sambil menyodorkan segelas teh hangat yang masih menyisahkan uap putih lembut.
“Terima kasih untuk tehnya, Bu.”
“Ibu di sini siap mendengarkan semua keluh kesahmu. Ceritakan saja apa yang ada di hatimu,” sambung Ibu, lalu duduk di sebelah Ira dengan penuh perhatian. Matanya kontak dengan Ira, sambil melempar selembar senyuman.
“Sebenarnya, aku hanya merasa frustasi,” kelunya Ira.
Setiap kali mengikuti lomba entah itu esai, artikel, puisi, ataupun cerpen hasilnya selalu mengecewakan. Ira berkeluh kesah. Ibunya tetap menatap wajah anaknya yang terus menerawang bersama garis angin.
“Seolah-olah kebahagiaan itu tidak ditakdirkan Allah untukku. Padahal aku sudah berusaha sebaik mungkin dan selalu berdoa agar bisa menjadi pemenang. Aku kurang apa, Bu?” ujar Ira dengan suara melemas, menahan air mata di ujung mata yang hampir jatuh.
“Nduk, Ibu tahu betapa sulitnya yang kamu alami,” Ibunya menasihati.
Baca juga: Kidung Wahyu Kolosebo
“Pertama-tama, jangan pernah berkata bahwa Allah tidak memberikan kebahagiaan untukmu,” Katanya ke Ira dengan lembut.
“Tapi bagaimana, Bu? Aku selalu gagal di semua perlombaan,” balas Ira, suaranya penuh kepasrahan.
“Ira, maukah kamu jalan-jalan pagi bersama Ibu? Tapi, tolong ambilkan dua genggam garam dan satu gelas dulu,” tawar Ibu dengan senyum.
“Jalan-jalan sih, ayo saja, Bu. Tapi garam dan gelas itu untuk apa?” tanya Ira, merasa bingung.
“Sudah, turuti permintaan Ibu dulu,” tegas Ibu dengan mata penuh harapan.
Ira pun berjalan menuju dapur untuk mengambil barang-barang yang diminta oleh Ibu, meski rasa penasarannya semakin membesar.
Mereka berjalan menuju sungai jernih, di mana mata air mengalir segar. Ira semakin penasaran dengan suruhan Ibunya membawa garam dan gelas. Ira berpikir, ibunya mengajak bersantai sambil mandi di sungai.
Ira mengikuti setiap langkah ibunya, sambil mendung dalam pikirannya berhenti di stasiun yang dia mimpikan.
“Nduk, letakkan garam di kedua tanganmu di batu besar ini!” perintah ibu.
“Pisahkan, lalu isi gelas dengan air,” lanjutnya. Ira masih bingung dengan arahan yang disampaikan ibunya.
“Iya, Bu,” jawab Ira cepat. Dia meletakkan garam dan mengisi gelas.
“Masukkan segenggam garam pertama ke dalam gelasmu. Aduk, lalu cicipi,” perintahnya.
Ira mengikuti instruksi, lalu mencicipi airnya.
“Bruuuuuuuuuuuuus! Cuih… cuih… cuih…! Asiiin, Bu!” serunya saat mencicipi. Wajahnya berkerut.
“Nah, sekarang ambil segenggam garam kedua dan lemparkan ke danau di depan kita,” perintah Ibu. Ira pun melemparkan garam itu dengan sekuat tenaga ke arah danau.
Baca Juga: Lurah Jadug
“Sudah, Bu.”
“Kalau sudah, coba minum air danau itu. Segar, kan?”
Tanpa ragu, Ira langsung meneguk air danau. Rasanya tak berubah sama sekali. Ira terus minum karena kesegarannya, ingin menghilangkan dahaganya.
“Kamu paham maknanya, Nduk?” tanya Ibu lembut.
“Tidak, Bu. Aku masih bingung,” jawab Ira dengan wajah menunjukkan kebingungan.
“Bayangkan garam itu sebagai cobaan dari Allah yang sering kamu keluhkan,” ibunya menjelaskan.
Gelas kecil ini mewakili hatimu yang sempit, sehingga cobaan terasa sangat berat, sambungnya. Sebaliknya, danau yang luas dan dalam melambangkan hati yang lapang. Jika cobaan dimasukkan ke hati yang luas, dia tidak akan terasa berat dan malah bisa memberi kesegaran.
“Jadi, masalahmu bukan pada cobaan itu sendiri, tetapi pada cara kamu menerima cobaan.” Ira memandang ibunya dengan pasti.
Jika hatimu seluas danau, kamu tidak akan merasa sedih atau lemah. Pilihan ada pada hatimu yang sempit atau yang luas.
Matanya berair. Air matanya mulai menetes. Sesekali matanya dipejamkan.
“Yuk, kita kembali ke rumah! Ibu sudah menyiapkan kabar gembira,” sambung Ibu semangat.
“Tadi, Ibu mendapat info tentang lomba puisi. Kamu harus ikut, ya! Ibu yakin, kamu pasti bisa melakukannya.”
Ira memandang wajah ibunya yang menyembur cahaya. Air matanya masih membekas di pipi. Senyumnya masih belum merekah.
“Ayo,” ajak ibu sambil mengulurkan kedua tangannya. Ira pun menyambut.
Baca juga: Ada Jenderal Mati di Pasar
*
Meskipun begitu, rasa takut kembali menghantuinya.
“Apa yang bisa aku tulis yang layak?” pikir Lembahira.
Dia merasa terjebak dalam bayang-bayang ketidakpastian. Namun, lingkungannya yang selalu mendukungnya, termasuk Ibu, terus mendorongnya untuk mencoba.
“Tulislah dari hati, Lembahira! Jangan terlalu memikirkan hasilnya,” kata Ibu penuh keyakinan.
“Tapi, Bu, kalau nanti tidak diterima?” tanya Ira, masih ragu.
“Yang penting kamu sudah berusaha. Setiap kata yang kamu tulis adalah bagian dari dirimu,” jawab Ibu, menepuk bahunya. Ira menatap kembali wajah putih ibunya.
Dengan rangkaian semangat baru, Ira mulai menulis. Dia menuangkan semua kisah dan impian yang terpendam ke dalam puisi. Menyalurkan segala kerinduan dan harapan yang ada di hati.
Jemari Lembahira digerak.
Mengumpulkan keberanian yang pernah hilang. Menuliskan kegalauan yang selama ini bersemayam. Rindu dan keinginan dirajut. Mimpi dan keinginan kembali menyala.
Lembahira terus menelusuri relung, kelokan, dan bermukim di lembah yang selama ini asing. Dia mulai menyapa kembali. Senyumnya kembali dihimpun. Menjadi tebing-tebing yang siap membentengi ketakutan yang selama ini mengungkungnya.
“Assalamualaikum hati yang bergerak,” ucap Ira menyemangati diri kala deretan kata menjadi kalimat terus mengucur dalam naskah puisinya.
Lembahira terus melaju bersama asa yang meraja. Hembusan angin masuk melewati fentilasi terbuka di atas pintu. Ain merambat. Di luar sana, daun pohon jati masih kukuh oleh terpaan angin di medio sore ini.
“Semoga, naskah puisi ini yang terbaik,” Ira menghela napas.
Ibu Lembahira membalas dengan irama senyum bernuansa.
Baca juga: Tarko
*
Beberapa minggu kemudian, saat pengumuman pemenang lomba tiba, Ira duduk di depan radio dengan rasa cemas menyelimuti hatinya. Jantungnya berdebar kencang, setiap detik terasa seperti satu jam.
“Pemenang pertama diperoleh atas nama Lembahira!” suara yang terlontar dari radio membuat Ira tertegun sejenak, tidak percaya.
Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Sorakan keluarga menggema di telinganya, menciptakan momen yang tak terlupakan. Karya yang selama ini dipenuhi keraguan akhirnya diakui.
“Kamu memiliki potensi yang luar biasa. Teruslah menulis Lembahira! Karena dunia sangat membutuhkan suara sepertimu,” ujar Ibu, matanya bersinar bangga.
Kata-kata itu seperti embun di pagi hari, menyegarkan jiwa dan menyalakan semangat baru dalam dirinya. Kemenangannya bukan hanya tentang trofi atau penghargaan ini adalah pengakuan atas keberanian untuk mengejar impian meski dikelilingi penolakan.
Kini, dengan pena di tangan dan hati yang penuh harapan, Ira siap menulis bab-bab baru dalam hidupnya, mewujudkan setiap impian yang telah lama terpendam. Dia tahu, setiap kata yang ditulisnya adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. (#)
Penyunting Ichwan Arif