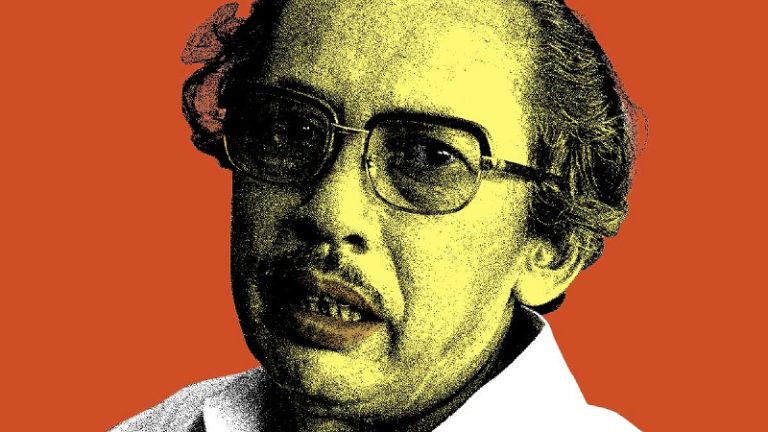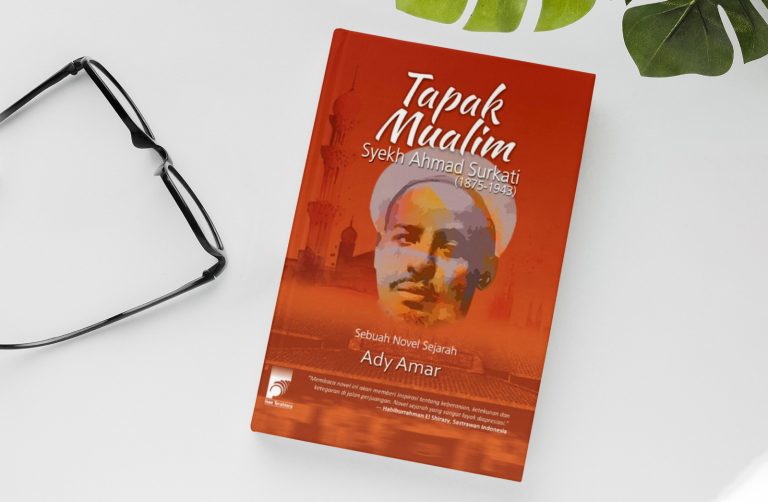Aku telah merasakan penderitaan setelah divonis dokter THT pita suara rusak. Tapi, anehnya vonis ini malah membuat tetangga, teman-teman, klien, hingga atasan dan bawahanku menganggap lain.
Cerpen oleh Bekti Sawiji, ASN di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Jawa Timur
Tagar.co – Vonis dokter THT membuat aku bagaikan tersengat listrik dengan tegangan ultra tinggi. Dia mengatakan bahwa aku menderita vocal chord paralysis alias kelumpuhan pita suara.
Memang beberapa hari itu, aku mengeluh kesulitan bicara. Aku rasa setiap orang juga pernah mengalami kesulitan berbicara atau mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa.
Itu biasanya terjadi setelah kita mengeluarkan bunyi-bunyi yang berlebihan seperti berteriak-teriak, menyanyi dengan suara keras dan lama. Tetapi, yang terjadi padaku cukup aneh karena sebelumnya aku tidak pernah bernyanyi apalagi berteriak. Hal itu terus membuat aku galau.
“Bu Roman, bersyukur pita suara Ibu yang sebelah masih sehat dan berfungsi dengan baik,” begitu ucap dokter kala itu.
“Tidak ada kaitan langsung antara pita suara yang satu dengan yang lain, artinya jika tidak terjadi sesuatu, pita suara yang sehat itu akan aman,” lanjutnya.
Hanya dengan pita suara sebelah yang sehat, sejak pulang dari THT itu, suaraku menjadi semakin lemah, seperti orang yang berbisik. Orang-orang di rumah juga merasakan dampaknya.
Mereka kesulitan mendengar panggilan, pertanyaan, atau penjelasan dariku. Mereka harus mendekati dan memperhatikan aku dengan baik untuk memahami apa yang kuutarakan.
Baca juga: Jalan Kembali
Ini tentu meresahkanku dan keluarga, apalagi makin lama pita suaraku yang sehat ikut-ikutan melemah. Praktis beberapa minggu kemudian, aku menderita. Bukan lagi kelumpuhan pita suara unilateral, melainkan bilateral, yaitu lumpuhnya kedua pita suara.
Jika anggota keluargaku resah dengan hilangnya kemampuanku berbicara, maka tidak demikian dengan tetangga, teman-teman, klien, hingga atasan dan bawahanku. Aku merasa mereka tidak berempati atas musibah yang kualami. Justru, mereka terlihat senang dengan keadaanku.
Bukannya tanpa alasan, mereka senang dengan penderitaanku karena kebanyakan dari mereka ada korban dari mulut pedasku. Itu sangat kusadari. Lebih tepatnya aku sadar setelah menderita kelainan ini.
Sering aku merenungkan perilakuku yang menyakiti hati orang lain dengan kata-kata. Seperti suatu ketika, aku memarahi seorang pemuda petugas kebersihan kantor.
“Hei, kantor rugi membayar kamu kalau pekerjaanmu tidak beres. Coba lihat mejaku ini, sudah berapa tahun tidak kamu lap? Debunya… uh ampun deh,” cerocosku hiperbolis.
Buru-buru pemuda mendekat dan momohon maaf lalu mengelap meja aku. Atau suatu hari aku memarahi klien yang mengajukan kredit, “Mana mungkin rumah sekecil dan sejelek ini, Bapak ajukan sebagai agunan dengan plafon 100 juta. Mustinya Bapak membuat penilaian terlebih dahulu sebelum mengajukan. Bisa tanya ke teman kek, atau baca-baca dulu di internet. Belum lagi berapa penghasilan Bapak.”
Baca juga: Ayah Kecil dan Benda Mirip Delima
Tanpa menjawab sepatah katapun, bapak itu berdiri, memungut sertifikat rumahnya dan berkas-berkas lainnya di meja, balik kanan dan pergi tanpa pamit. Seluruh isi ruangan memandang aku tetapi tidak ada yang berani berkata-kata.
Dengan santai, aku melanjutkan pekerjaan tanpa memedulikan teman-teman dan bapak tadi. Dengan begitu kantorku kehilangan potensi pelanggan kredit.
Di hari yang lain, aku pernah menasihati seorang perempuan 29 tahun yang bekerja di kantorku dan belum menikah. Dia cantik tetapi pendiam. Tanpa dia minta, aku mulai menceramahinya.
“Monik, kamu tidak ingin segera kawin kah? Kamu cantik loh. Tapi apa gunanya cantik kalau sampai segini tua kamu belum laku juga. Sebaiknya kamu gak usah pilih-pilihlah. Kamu juga jangan cerewet karena laki-laki tidak suka kepada perempuan yang banyak bicara, apalagi bicaranya ketus, pedas, dan gak sopan. Oh ya, apa sejauh ini sudah adakah lelaki yang mendekati kamu? Seusiamu ini jangan idealis Monik. Misal gak menemukan perjaka, duda pun gak masalah loh, yang penting laakuu!”
Monik beranjak pergi dengan tidak memedulikan aku. Aku tersenyum melihat kelakuan dia. Teman-teman seruangan diam atau pura-pura diam melihat situasi itu.
Jika di dunia nyata aku judes, di dunia maya aku relatif diam. Meskipun suka berbicara pedas kepada orang-orang yang berhubungan denganku, aku jarang sekali atau hampir tidak pernah berbicara atau berhubungan dengan orang di media sosial.
Baca juga: Insomnia
Aku tidak memiliki akun Facebook, Instagram, X, apalagi TikTok. Aku malas berhubungan dengan orang-orang di sana. Lebih tepatnya aku agak gagap teknologi. Lebih dari itu aku juga malas mengetik karena jemariku teramat kaku dan besar-besar untuk mengetik di papan ketik yang mungil itu.
Whatsapp saja lebih banyak aku gunakan untuk menelepon dan pesan suara. Mungkin usiaku yang sudah lebih dari setengah abad ini yang semakin membuatku sulit untuk menyesuaikan diri dengan teknologi. Andai aku paham teknologi dan menguasai literasi digital, mungkin aku menulis perkataan-perkataan yang pedas juga.
Kini tidak ada penderitaan yang pedih selain mendapati diriku sudah tidak bisa menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Mungkin akukah orang yang bisu itu?
Tak terasa, malam-malam ku isi dengan tangis dan derai air mata. Melalui lekuk dan guratan di pipi lalu jatuh ke dada, air mata itu menetes bagai hujan. Hatiku perih bagai ditusuk-tusuk oleh jarum.
Dalam kondisi duka seperti itu, aku mulai mendekatkan diri kepada sang Pencipta. Aku tahu bahwa Tuhan bisa mendengar potongan-potongan doa yang ku serukan, meskipun lisanku terdiam.
Beberapa bulan aku hidup tanpa kata, tanpa bicara. Tuhan benar-benar merantai organ wicaraku untuk mengartikulasikan letupan atau hembusan vokal dan konsonan di rongga dada sampai rongga mulut.
Baca juga: Dorbok!
Percuma aku hembuskan napas, menggerakkan ujung lidah ke langit-langit mulut, atau menghantamkannya ke sisi belakang gigi atas dan bawahku. Semua tidak menghasilkan bunyi sama sekali bahkan sekadar bisikan tidak mampu kuhasilkan.
Beban ini semakin terasa tatkala kesukaan bicara pedasku tertawan, tidak ada cara untuk menumpahkan kebiasaan itu. Andaikan masih normal, mungkin aku sudah menceramahi, mengata-ngatai, dan menghina banyak orang. Tetapi aku tidak putus asa dan mengikuti saran dokter untuk mengambil sesi terapi wicara di sebuah klinik.
Aku kembali mendatangi klinik terapi wicara untuk kesekian kalinya. Dokter terapis itu menyapaku dengan ramah.
“Sehat, Bu Roman?” sapanya yang ku balas dengan senyum tipis dengan enggan.
Dia menyilakanku duduk di kursi pasien dan setelah sedikit pengantar. Dia memintaku membuka mulut. Kemudian mulai melakukan prosedur terapi oral. Sesekali dia memasukkan oral motor tool.
Dia juga memintaku untuk menjulurkan lidah dalam beberapa hitungan, mengerucutkan mulut, dan menghembuskan napas. Melelahkan dan membosankan. Dan lagi, hasilnya nihil.
Baca juga: Lurah Jadug
Ingin sekali marah dan mengomeli dokter ini. Sayang, saat ini mustahil bagiku untuk melakukan itu semua. Mungkin suatu saat, ketika kelumpuhan pita suaraku ini pulih kembali, dan entah kapan.
Dokter itu melihat aku yang sedih dan gelisah. Dia melihat aku seperti ingin berbicara tetapi tidak bisa. Dia melihat ada asa yang hilang di wajahku. Seperti paham, dokter itu bangkit untuk mengambil secarik kertas dan pena di almarinya. Lantas dia menyodorkan kertas dan pena itu kepadaku dan menyilakan aku untuk mengatakan sesuatu melalui tulisan.
Tanpa basa-basi, akupun mulai mencorat-coret kertas putih itu untuk membuat tulisan. Aku melihat dokter tersenyum bahagia melihat aku bersemangat menulis. Dengan sabar, dia menunggu tulisanku. Begitu selesai, aku pegang kertas itu, dengan bernapas besar aku menyerahkan kertas itu ke dokter.
Lalu dokter itu mulai membaca dalam hati tulisanku yang berbunyi: “DOKTER!!! Anda bisa bekerja apa tidak sebenarnya? Apa background spesialisasi Anda? Mengapa menangani saya tidak serius? Seharusnya Anda bekerja profesional dong. Heran saya, mengapa dokter seperti Anda lulus kuliah.”
Aku meninggalkan dokter yang bengong itu dengan perasaan puas. (#)
Lumajang, 22 Agustus 2024
Penyunting Ichwan Arif