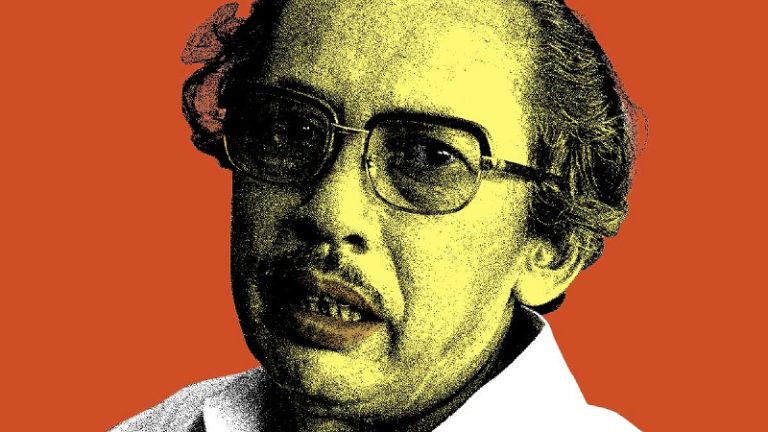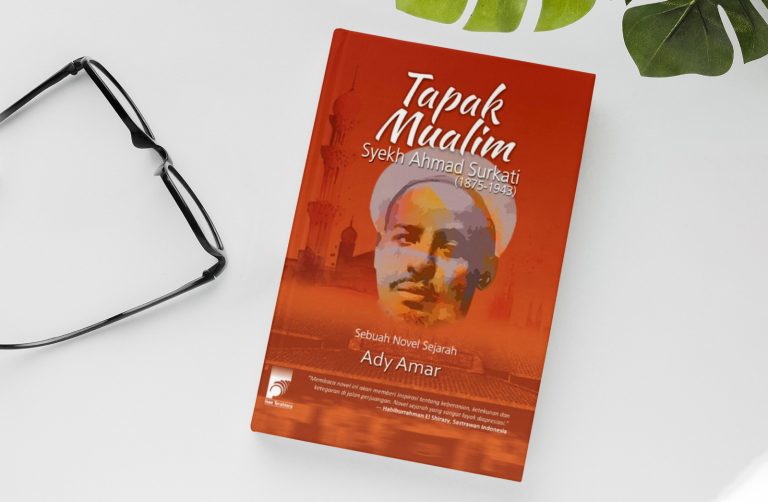Di mata warga, Pak Tua adalah lusuh, kotor, dan bau. Mereka melihatnya dengan sinis. Ketika anak-anak melemparnya dengan kerikil, Pak Tua itu hanya tersenyum dan memberikan permen.
Cerpen oleh Risha Iffatur Rahmah, pendidik di SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Sidoarjo
Tagar.co – Matahari dengan apinya, perlahan membungkus cahaya. Siapa pun tak akan mampu melihatnya bahkan dari kejauhan. Mereka masih membutuhkan tangan atau kacamata hitam. Namun, di naungan pohon ada tempat berlindung nan sejuk. Pak Tua tidur di sana.
Lelaki itu merebahkan badannya sambil menerka jangkauan cahaya di sela tangannya. Langit begitu cerah diiringi angin kering dan gersang. Angin yang lembut tapi membawa dahaga. Pak Tua hanya terdiam.
Hari mulai sore, kembalinya Pak Tua membuat orang hafal bagaimana ia beristirahat siang di pematang sawah. Ada yang menyapa atau melirik sinis terlebih memandang lusuh, kotor, dan bau.
Raut petani itu hanya tersenyum tipis. Langkah kakinya begitu santai menembus pelataran rumah warga. Di ujung gang yang sepi, ia mulai membersihkan diri dan berganti pakaian. Tepat di sebelah masjid.
Marbot tidak bisa berbuat banyak, setiap dia datang selalu mengotori halaman. Pak Tua hanya tersenyum sesekali menggosok jejak lumpurnya. Si marbot juga punya kemanusiaan, akan tetapi rasa itu semakin pudar. Tepat di sore menjelang Magrib, dia mengomel. Tukang bakso lewat, segera Pak Tua memanggil dan mentraktir makan si marbot.
Baca juga: Ayah Kecil dan Benda Mirip Delima
“Saya marah, Pak. Setiap hari begini? Apa tidak ada kerjaan lain! Capek, Pak. Mengepel dan menyiram lagi!”
“Makan dulu! Satu porsi lagi Kang!”
Mereka makan bakso bersama, sebelum dua puluh lima menit azan Magrib berkumandang. Marbot begitu lahap sambil meminta lontong dan minuman.
Mungkin itulah kenapa dia marah. Bakso mereka habis dalam lima menit. Pak Tua tak banyak bicara hanya menepuk pundak. Di saat Pak Tua berlalu, badannya tercium wangi dan tampak bersih bersahaja. Marbot hanya tertegun lalu berwudu dan azan.
Masjid tua yang dari dulu dibangun oleh warga desa memang peruntukannya memfasilitasi warga tani guna membersihkan diri dan beribadah. Hanya saja, seiring waktu yang menua, masjid beralih dan berdalih. Masing-masing mata tidak suka rutinitas petani yang membersihkan diri.
Kebanyakan mata sinis adalah pendatang baru dari desa yang jauh. Merantau mendekati kota. Supaya tak mahal biaya hidupnya mereka memilih tempat ini. Seperti pengasingan yang berharap hidup enak nyaman dan damai.
Sementara itu, kebiasaan mereka hanya mengumpat dan membeda-bedakan kasta sosial. Kebanggaan bekerja di kota membuat mereka seperti malaikat kesiangan. Mencari wajahnya dan rayuannya ke sana ke mari. Tak kalah, si marbot yang juga asisten Bu RT. Sosok Bu RT tak lain istri dari pegawai minyak yang hobi pamer.
Pernah suatu hari ketika akan diadakan ruwat desa, ia bertemu Pak Tua. Mata kejam itu melirik dari bawa ke atas lalu memicingkan bibirnya ke bawah. Entah apa di pikirannya. Pak Tua hanya mengucapkan salam. Apa daya mulut Bu RT hanya komat-kamit tidak jelas.
Baca juga: Insomnia
Marbot yang menyaksikan kejadian ini terlihat bangga dan tersenyum puas. Padahal, jika dihitung, si marbot setiap sore selalu makan bersama Pak Tua. Ya, mungkin sudah disogok makanan yang lebih enak. Terbukti dari mengembangnya berat badan marbot. Sedangkan Pak Tua semakin ringkih.
Omongan warga desa baru semakin lama berasa pedas. Semua mencaci baju lusuh dan kotor petani itu. Anak mereka dididik mencemoh bau pesing atau amis. Ada yang berteriak dan melempari krikil. Pak Tua hanya tersenyum dan memberikan permen. Anehnya, mereka menerima permen dengan senang hati, seakan tidak terjadi apa-apa.
Semakin hari, Pak Tua menjadi sangat renta. Terkadang batuk dan berjalan memapah tembok dan meninggalkan bekas tangan. Orang-orang semakin geram. Dari kejauhan, ada pemuda yang sengaja menyiram Pak Tua.
Tubuhnya semakin mengigil dingin. Ia hanya tersenyum kembali. Di dalam hatinya, hanya berdoa agar Dang Tuhan memberikan keteguhan iman dan amal saleh.
Sesampainya di pelataran masjid, ia didorong oleh marbot. Terusirlah. Raut wajahnya semakin sedih. Banyak mata memandang di sore itu. Mereka diam tak mau menolong.
Baca juga: Dorbok!
Pak Tua kembali ke sawah. Ia ingat masih ada tampungan air hujan di tengah pematang. Sambil memungut tas ranselnya, ia bergegas meskipun tenaganya hanya sedikit.
Dalam perjalanan, ia tak berani memegang tembok, pagar atau apa pun itu. Yang ia pegang hanya tanah atau jalan sambil merangkak. Tak satu pun iba dengannya. Jaraknya masih 1 km lagi di depan, sedangkan azan Magrib akan berkumandang 10 menit lagi.
Pak Tua tetap semangat. Ia tak begitu mempedulikan. Matahari pun lelah. Hanya kelelawar yang menemani. Sesampainya di sana, Pak Tua sibuk membersihkan diri meskipun angin dingin begitu kejam menusuk.
Ia mendirikan salat di tengah pematang sawah yang kering. Dalam sujud terakhirnya ada malaikat yang menemani, lalu berbisik dan terdengar samar kalimat syahadat dari Pak Tua.
Ya, Pak Tua wafat di tengah sawah miliknya sendiri. Sawah yang begitu luas dan tidak ada orang yang menyewa bahkan para pekerja. Sawah itu hanya ditumbuhi padi dan ilalang. Ada yang basah dan kering.
Kesendiriannya dimulai sebulan lalu, ketika istrinya sudah berpulang terlebih dahulu. Sedangkan anak-anaknya merantau tidak tahu kabarnya.
Hembusan angin perlahan-lahan di tengah malam menjadi saksi bagaimana jasad orang bersujud di tengah pematang sawah. Terlihat ia terbuang sendiri dan dikucilkan. Tidak ada satu pun mencari keberadaanya. Malam semakin larut berganti pagi, siang, sore, dan malam. Sampai sepekan kemudian tidak ada yang menyadari.
Berbeda dengan kehidupan warga yang sedang asik bergunjing karena merasa senang tidak ada lagi Pak Tua yang mengotori halaman mereka. Rasa itu juga menghampiri si marbot yang merasa ringan pekerjaannya.
Baca juga: Lurah Jadug
Sampai akhirnya, tepat dua pekan setelah kematian Pak Tua, Pak Lurah dan perangkatnya berkunjung ke rumah Pak Tua untuk mendata lansia dengan bantuan khusus namun tidak ada siapa pun dan terlihat tak terawat. Banyak daun berguguran di teras dan pintu rumahnya tertutup rapat. Di sana tidak ada satu pun tetangga yang mau untuk ditanyai atau mengabarkan.
“Mungkin masih di sawahnya Pak! Sawahnya begitu luas, di dekat masjid tidak jauh dari sini.”
Mereka bergegas. Bertemulah si marbot. Dia hanya menyapa dan menggelengkan muka saat ditanya. Langkah empat orang menyusuri sawah.
“Kita tahu Pak, luas tanah Pak Hartoyo dimulai dari masjid tadi sampai ujung pematang sawah dekat penampungan air hujan. Sayang sekali, kekayaan yang seperti ini tidak terkelola oleh anaknya. Semua minggat! Seperti kelakuan warga yang memilih merantau ke kota!” ujar salah satu perangkat desa.
“Ya, ini sampai kapan kita jalan!”
“Ya, bentar lagi Pak. Kita akan sampai pada pohon kapuk pinggir pematang yang ada tampungan air hujan.”
Langkah mereka dipercepat karena sudah terlihat Pak Tua yang bersujud.
“Barangkali. Kita tunggu selesai salat.”
“Nah, kok gosong!” Itulah yang terlihat di kedua tangan dan telapak kaki Pak Tua.
Mereka segera berlari menghampiri. Sambil terengah-engah, mereka menyimpulkan Pak Tua telah wafat sudah lama. Jasadnya mengering dan tidak berbau. Kulitnya gosong dan keriput seperti ikan asin. Kabar duka itu sampailah ke warga desa.
Baca juga: Lurah Jadug
Perangkat kelurahan menyalahkan semua warga yang menjadi tetangga Pak Tua. Padahal semua aset yang mereka miliki berdiri di lahan Pak Tua. Lahan yang sengaja diwakafkan. Pak Lurah juga memarahi si marbot dan Bu RT yang membiarkan orang salat di tengah pematang sawah, sedangkan masjid itu milik Pak Tua.
Di tengah pemakaman, Pak Lurah mengusir warga pendatang. Ia tak peduli dengan mereka. Izin tinggalnya dicabut. Wakaf tanahnya dikembalikan lagi kepada desa dan masyarakat yang tidak punya hati itu diusir paksa. Anehnya, dari mereka ialah keluarga kaya raya, pemerhati lingkungan, dan pegawai pemerintahan.
Tidak satu pun dari mereka memiliki rasa kemanusiaan. Hanya Pak Tua yang perhatian dengan lingkungan persawahan dan aliran sungai. Sungai yang tetap bersih walaupun Pak Lurah tahu setiap pekan Pak Tua memungut sampah yang sengaja dibuang oleh warga pendatang.
Sekarang, tugas Pak Lurah semakin berat, apalagi jumlah warganya semakin sedikit. Mereka harus terjun menjadi Pak Tua. Mengelola tanah wakaf, harta Pak Tua, serta melestarikan lingkungan. Pak Lurah ingat betul bagaimana akad wakaf dan janji yang diucapkan.
“Jika kebaikan bapak dan keluarga ini tidak disambut baik oleh warga, maka kami sendiri yang akan bertindak.” Ucapan itu sekarang terbukti, hanya tersisa 17 kepala keluarga asli dan selamanya tetap 17. (#)
21 Agustus 2024
Penyunting Ichwan Arif