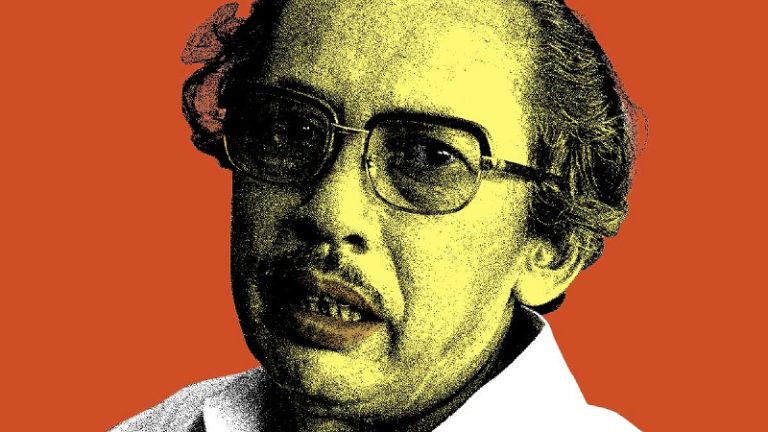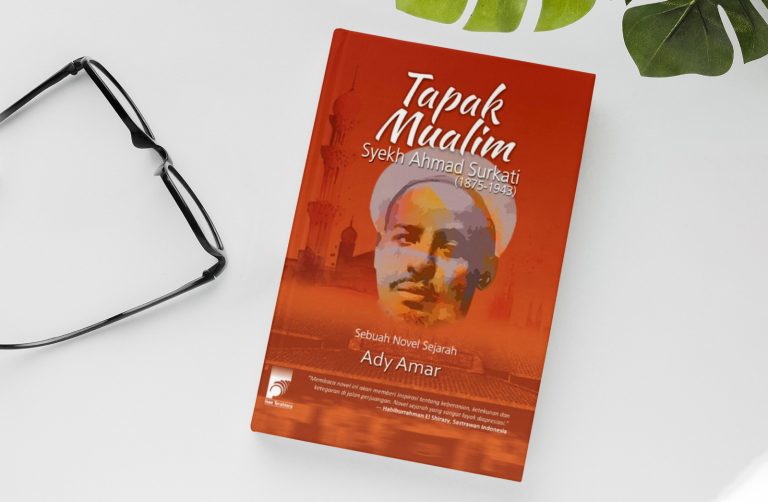Ketegaran hidup ayah menurun sejak ibu wafat. Aku pun berniat akan membersamai ayah selepas wisuda. Satu pesan ayah terus kupegang, jangan berjalan di pinggir jurang jika tak ingin jatuh ke dalamnya.
Cerpen oleh Kamas Tontowi, Ketua Majelis Pendidikan Kader dan Sumber Daya Insani PDM Trenggalek dan guru bahasa Inggris MTsN 3 Trenggalek
Tagar.co – Hari terasa cerah. Ayah menyaksikan berita krisis moneter di televisi hitam putih di ruang tengah. Entah apa sedang direnungkannya. Beliau sudah sangat tua, bukan hanya umur, tapi pengalaman kehidupan. Semua terlihat dalam tatap matanya.
“Le, sini kamu!” Beliau tiba-tiba memanggilku.
Tanpa menyahut, aku duduk di dekat beliau.
“Apa beda suci dan bersih?” tanya ayah, tiba-tiba.
“Bersih belum tentu suci, suci belum tentu bersih,” jawabku, sesuai dengan kemampuan, di balik kebodohan yang kumiliki.
Ayah diam saja. Tidak ada sepatah kata pun terucap dari bibirnya. Aku yang kikuk, menunggu beberapa saat. Lantas aku beringsut dari kursi dengan malu-malu.
“Ayah, maafkan anakmu ini. Suatu saat engkau akan bangga denganku. Meskipun, apabila engkau sudah tidak di dunia ini. Maafkan aku terlalu sering menjadi beban hidupmu,” ungkapku dalam batin.
Ayah beberapa waktu ini sering sakit-sakitan. Ketegaran hidupnya sudah menurun sejak ibu meninggalkan kami.
Baca juga: Pemilihan Ketua RT
Waktu terus berlalu. Sebagai mahasiswa akhir, aku harus segera kembali ke Malang. Menuntaskan SKS tersisa dan skripsi selama satu semester. Setelah selesai, aku berniat segera pulang ke rumah. Menemani ayah yang sakit.
Setengah tahun terlampaui. Aku harus meninggalkan kota dingin Malang menuju kota lama, tempat stasiun kereta api. Sampai di kota lama, aku segera beli tiket kereta api dan menunggu kereta berangkat. Kalau dulu, beli tiket tidak secara online, tapi langsung di loket.
Setelah dua jam di ruang tunggu, aku masuk ke dalam kereta api. Terlihat beberapa orang sudah menempati tempat duduk di dalam kereta. Selain diriku juga masih banyak penumpang mahasiswa yang berniat pulang ke rumah sekadar untuk mengambil uang dan kangen keluarga.
Terlihat beberapa penjual menjajakan dagangannya. Mulai dari pedagang minuman, makanan bahkan pengamen. Mereka bergantian mendatangi kami untuk mencari nafkah. Terlihat seorang pedagang ketela matang.
“Monggo-monggo telo godok,” tawar penjual separo baya itu dalam bahasa Jawa.
“Lumayan ketela itu, beli dua sudah membuat perutku penuh, lumayan untuk mengisi perut. Murah meriah yang penting kenyang,” batinku.
“Berapa satu, Mas?” tanyaku.
“Lima ratus, Mas,” jawabnya.
Pada waktu itu, tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, harga ketela godog masih lima ratus, seharga air mineral gelas.
“Ohhh ya saya beli dua, tambah satu gelas air mineral, biar bisa melancarkan jalannya ketela ke perut. Lumayan. Murah meriah,” basa-basiku.
“Ohh ya, Mas. Seribu lima ratus totalnya. Makasih, Mas ya. Laris, laris, laris, berkah.” Penjual ketela terlihat gembira.
Baca juga: Jangan Biarkan Aku Kufur Nikmat
Kereta pelan-pelan berjalan menuju ke arah barat. Menuju Kota Blitar, dan Tulungagung. Aku segera menuju pintu, menikmati indahnya perjalanan. Sawah terhampar luas, orang-orang di jalan raya yang mobilnya terlihat beradu kecepatan dengan kereta api.
Sesekali terdengar para pengamen menjajakan suaranya. Aku cuek saja. Aku segera beringsut ketika tukang karcis kereta api meminta karcis padaku. Tangannya menjulur ke diriku tanpa kata-kata.
Aku paham. Dia minta bukti karcis. Segera kuberikan padanya. Dia menyobek separo karcisku, tanda sudah dicek petugas.
Sesampai di Sumbergempol Tulungagung, aku turun dan menuju jalan raya untuk menunggu bus ke arah terminal. Bus Harapan Jaya datang dan aku segera masuk.
Seorang lelaki berseragam merah merah, seragam khas kondektur mendatangiku.
“Ke mana, Mas?” tanya kondektur.
“Trenggalek, Pak,” jawabku singkat.
“Ohhh, bablas mawon nggih. Kami langsung ke Trenggalek.” Dia menasihatiku.
“Nggih. Nanti turun Kamulan,” aku mengingatkan.
“Siap,” jawabnya singkat.
Beberapa saat kemudian, aku turun di Durenan dan menuju ke rumah naik angkutan kol ke rumahku. Berjarak sekitar lima kilo dari Pasar Kamulan.
Sesampai di rumah aku menuju ke kamar bapak. Terlihat beliau tersenyum bahagia sambil berbaring di dipan ditambah kasur buatan tetangga.
“Sudah sampai, Nak. Alhamdulillah,” ungkap ayah
“Nggih pak. Alhamdulillah. Aku sudah selesai bab empat, Pak. Tinggal bab lima. Akhir Desember tahun ini aku bisa wisuda,“ sambungku.
“Alhamdulilah. Hati-hati menjalani hidup, Nak ya. Jangan berjalan di pinggir jurang jika kamu tak ingin jatuh ke dalamnya,” pesan bapak.
Waktu terus berjalan. Sakit ayah semakin parah. Tubuhnya terbaring miring menghadap ke barat, seolah-olah ayah siap untuk menghadap Illahi. Kakak-kakakku tak bosan-bosan mentalqin ayah agar menghembuskan napas terakhir dengan kalimat ‘Allah’.
Baca juga: Saat sang Cerpenis Stres
Aku setiap hari menunggunya. Terutama malam. Menjelang subuh, aku tiba-tiba menangis melihat ayah yang terbaring. Setengah badannya terasa dingin.
”Ya Allah, mudahkanlah urusan ayah. Bila sudah waktunya, segera ambillah ruhnya. Ya Allah, aku ikhlas,“ kataku lirih dalam hati.
Tiba-tiba aku melihat ayah seperti merasa sesak napas. Aku segera memanggil kakak. Aku segera ke luar kamar. Tidak kuat melihat sakit ayah.
Tak berapa lama, kakak perempuanku keluar.
”Le, ayah sudah kembali pada-Nya. Beberapa hari ini ayah tidak mau berpindah posisi. Beliau selalu tidur miring menghadap ke barat. Seolah-olah siap diambil ruhnya,” ucap kakaku terbata-bata.
Aku menarik napas dalam-dalam, sesekali melihat langit. “Ayah. Kau akan bangga padaku kelak. Ya Allah, terimalah ayahku di sisi-Mu. Dialah yang mengenalkan aku pada-Mu, ya Allah.” (#)
Penyunting Ichwan Arif