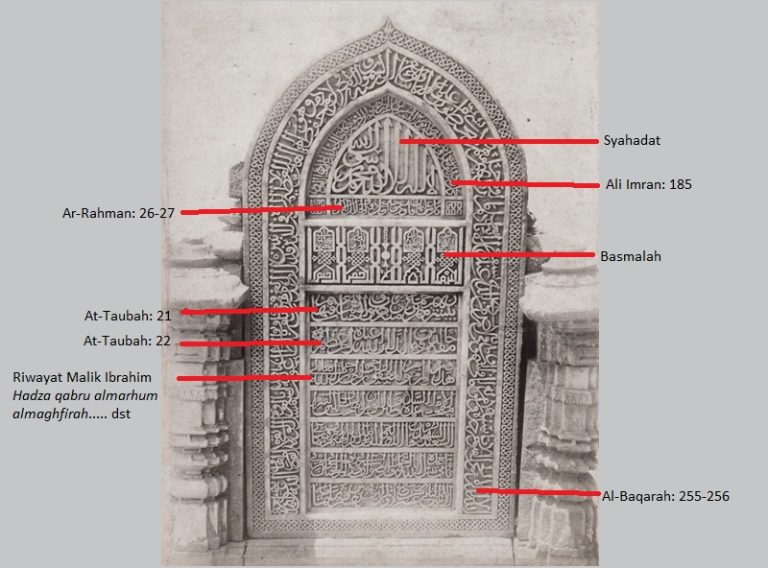Teladan kesederhanaan bisa kita peroleh dari pemimpin atau tokoh Islam Indonesia. Dari Haji Agus Salim, Mohammad Natsir, AR Fachruddin, Abdurrahman Wahid, Ahmad Syafii Ma’arif, hingga Haedar Natsir.
Tagar.co – Banyak tokoh Islam Indonesia dengan jabatan mentereng tapi hidupnya sederhana, bahkan supersederhana. Mereka patut menjadi teladan bangsa di tengah menguatkan gaya hidup hedon yang kadang ditempuh dengan cara kotor.
Sayangnya redaksi Tagar.co tidak bisa menampilkan banyak tokoh yang hidupnya sederhana dalam tulisan ini karena keterbatasan rang dan referensi. Berikut beberapa di antara yang kisahnya bisa dikutip.

Hidup Nomaden Haji Agus Salim
Seperti diceritakan oleh Anies Baswedan dalam kolom berjudul Kesederhanaan, Keteladanan yang Menggerakkan.
Selama di Jakarta, Agus Salim tinggal di satu rumah kontrakan ke kontrakan lain. Ia menjalani ‘pola nomaden’ ini bersama istri dan anak-anaknya. Ia misalnya pernah di sebuah rumah di Kawasan yang kini dikenal sebagai Jatinegara, Jakarta Timur.
“… keluarga Agus Salim hanya menempati satu ruangan. Koper bertumpuk-tumpuk di pinggir dan beberapa Kasur digulung,” kenang Mohammad Roem, seperti dikutip Anies Baswedan.
Dalam buku Agus Salim Diplomat Jenaka Penopang Republik Seri Buku Tempo: Bapak Bangsa (KPG, 2013),Siti Asiah, anak kedepalan Agus Salim, bercerita sejak bayi hingga remaja, ia dan keluarganya harus berpindah rumah puluhan kali. Bahkan ada kalanya keluarganya harus pindah rumah lebih dari satu kali dalam sebulan.
“Sebab, begitu keadaan lebih baik, ada penghasilan, pindah ke tempat lebih bagus,” kata Siti Asiah.
Dia menceritakan, keluarga Agus Salim sudah biasa pindah dari rumah kontrakan kecil sederhana ke rumah besar. Kalau keuangannya sedang tak bagus, mereka akan menyewa rumah lebih kecil.
Dia masih ingat suatu ketika keluarganya pindah ke sebuah rumah besar di Gang Nangka, Kwitang, Jakarta. “Kami pindah ke rumah itu karena keadaan kuangan ayah agak bagus,” kenangnya.
Baca juga: Homeschooling Inspiratif ala Haji Agus Salim
Dari Kwitang, keluarganya pindah lagi beberapa kali, antara lain ke Krukut, Jalan Karet, dan Jalan Gereja Theresia. Di rumah terakhir inilah pasangan Haji Agus Salim-Zainatun Nahar dan anak-anaknya menetap.
“Buat kami, rumahnya bukan jadi soal, yang penting berkumpul. Semua rumah itu baik,”,” katanya.
Keluarganya pernah tinggal cukup lama di Jalan Karet, Petamburan. Di rumah itu salah seorang kakak perempuannya menikah dan tinggal di sana bersama suaminya.
“Banyak sekali kamarnya, tujuh barangkali, seperti kereta api.”
Perempuan yang akrab disapa Bibsy ini mengatakan kakak tertuanya, Theodora Atia, yang akrab dipanggil Dolly, lahir di kampung ayahnya, Koto Gadang, pada Juni 1912. Dua tahun kemudian, anak kedua, Jusuf Tewfik Salim, lahir di Bogor. Sejak itu, keluarganya terus berpindah rumah dengan kondisi ibunya melahirkan setiap dua tahun.
Mereka tak cuma pindah di dalam Kota Jakarta, tapi hingga ke Majalengka, Surabaya, bahkan Madura. Ibunya, yang terbiasa tinggal bersama keluarga dan sepupu satu nenek, tiba-tiba mesti menetap di tempat asing jauh dari sanak kerabat. “Baru settle mesti pindah lagi, harus mulai kenalan lagi sama orang.”
Meski menjadi kaum ‘kontrakan’, ibunya tak mengeluh. Menurut Bibsy, orang tuanya tak pernah bertengkar atau memperlihatkan sedang susah di depan anak-anaknya. Setiap berkumpul, mereka selalu gembira dan menghibur anak-anaknya.
Menurut cucu Agus Salim, Agustanzil Sjahroezah, kakeknya sering pindah rumah karena dia tak kenal kompromi dan teguh memegang prinsip. Misalnya, kata dia, suatu ketika kakeknya bekerja sebagai redaktur di sebuah media, tapi keluar karena dilarang menulis tentang sesuatu hal. “Namun, syukurlah, masih ada yang bersedia menolong, menampung dia, istri, dan anak-anaknya,” ujar pria yang akrab disapa Ibong ini.
Putra Violet Hanifah-anak ketiga Agus Salim-ini mengatakan kakeknya sudah terbiasa hidup nomaden sebelum menetap di rumah di Jalan Gereja Theresia—kini Jalan KH Agus Salim Nomor 72.
Menurut Agustanzil, di rumah inilah Piagam Jakarta disusun. Hingga kakeknya meninggal pada 4 November 1954, rumah itu masih berstatus sewa. Anak-anak Salim kemudian patungan membelinya beberapa tahun kemudian setelah mereka hidup mapan.
Ketua Yayasan Hadji Agus Salim ini mengatakan Wakil Presiden Adam Malik pernah mengatakan kepada Presiden Soeharto agar pemerintah membeli rumah itu setelah neneknya meninggal pada 2 Desember 1977.
Soeharto mau membelinya, tapi rumah itu akan diratakan dan kemudian dibangun rumah baru. “Adam Malik tidak sepakat, bagaimana komentar dunia kalau presidennya sendiri yang membeli bangunan bersejarah dan kemudian menghancurkannya. Akhirnya Pak Harto tidak jadi membelinya,” ujarnya.
Baca juga: Diplomasi Jenaka Haji Agus Salim: Dari Jenggot hingga Pusar Adam
Rumah itu, kata Ibong, akhirnya dibeli seseorang dan dihancurkan juga. Kini di atas bekas rumah itu berdiri bangunan dua lantai berbenteng pagar tembok setinggi lebih dari dua meter. Pintu gerbangnya tertutup. Untuk memasuki rumah itu, pengunjung harus melewati pintu gerbang toko kue De’Panna di samping kanannya.
Fendi, yang mengaku bekerja pada pemilik rumah itu, enggan menyebutkan pemiliknya. Dia hanya mengatakan si empunya berada di luar negeri. “Rumah ini dulu memang rumah Agus Salim. Dibeli sekitar 1990. Sebelum dibeli sudah berpindah tangan beberapa kali,” ucapnya.
Menurut Agustanzil, Sukarno pernah memberi Salim sebuah rumah di Jalan Hanglekir I. Rumah itu pernah ditempati anak bungsunya, Mansur Abdur Rachman Ciddiq, tapi akhirnya dijual karena menjadi langganan banjir.
Kesaksian Mohamad Roem
Ihwal pindah-pindah rumah itu pernah disebutkan Mohamad Roem dalam Manusia dalam Kemelut Sejarah.
Pada suatu hari tahun 1925, dua pelajar Stovia, Kasman Singodimedjo dan Soeparno, mengajaknya ke ruma Agus Salim di Gang Tanah Tinggi Jakarta. Jarak asrama Stovia di Gang Kwini ke Tanah Tinggi ditempuh selam sepuluh menit dengan sepeda.
Dia menyatakan, jalan diaspal hanya sampai Stasiun Senen, selanjutnya jalan tanah penuh lubang.
“Lewat jalan ini dengan sepeda bagaikan naik perahu di atas air yang berombak,” kenang Roem.
Itulah kali pertama Roem bertemu dengan Salim. Ia tertarik pada salim karena berbeda dengan tokoh lain.
Rumahnya rumah kampung. Meja dan kursinya sangat sederhana. Sangat berlainan dengan apa yang saya bayangkan tentang seseorang yang sudah terkenal.” Roem kemudian hari menjadi sahabat keluarga Agus Salim.
Beberapa bulan setelah Roem berkenalan denga Salim, dia mendengar keluarga Agus Salim pindah ke gang Toapekong di Pintu Besi di depan Gereja Ayam, Jakarta.
Baca juga: Pergulatan di Balik Lahirnya Kementerian Agama
Menurut dia rumahnya tak kalah besar dari rumah di Tanah Tinggi. Di bagian luar ada meja dan kursi, tapi di dalam nyaris kosong. Ketika berkumpul di ruang dalam, mereka duduk di alas tikar.
“Rumah itu menunjukkan rumah keluarga yang kurang berada,” tulis Roem.
Beberapa bulan kemudian, keluarga rumah salim pindah lagi ke rumah temannya yang bekerja di sebuah surat kabar, Saeroen, di Mr Cornelis (Jatinegara). Menurut Roem, rumah itu lebih besar dan bagus, terletak di jalan lebih baik, tapi seluruh keluarganya tumplek-blek di satu ruangan.
Setelah tinggal beberapa tahun di situ, Salim pindah ke Bogor di sekolah swasta yang dibina Sarekat Islam. Dia Kembali ke Jakarta pada 1926 dan tinggal di Gang Lontar Satu. Rumahnya lebih sederhana daripada di tanah Tinggi dan Gang Toapekong.
“Penderitaannya ditunjukkan dalam hidup sederhana, yang kadang-kadang mendekati hidup dalam kekurangan dan kemiskinan,” Roem menulis.
Akibat Kritis pada Pemerintah Hindia Belanda
Dalam Seratus Tahun Haji Agus Salim (1984), Kustiniyati Mochtar menulis, dengan Pendidikan dan kemampuan tinggi, sebenarnya Agus salim dapat hidup enak bila mau bekerja untuk Pemerintah Hindia Belanda. Lantaran sikapnya yang kritis terhadap kebijakan pemerintah kolonial, ia kesulitan mencari nafkah.
Sejak keluar dari Bureau voor Werken atau Dinas Pekerjaan Umum pada 1912 dan memasuki dunia pergerakan setelah 1915, Salim hidup miskin. “Tak jarang mereka kekurangan uang belanja,” tulis Kustiniyati.
Zainatun, istri Salim yang mendapat panggilan sayang Maatje dari anak-anaknya, harus putar otak agar dapat memberi makan anak-anaknya.
Suatu Ketika Salim tak punya uang untuk membeli lauk-pauk. Ia tak kehabisan akal. Sa,bil bergurau, ia membuat nasi goreng. Dalam suasana ceria, mereka makan Bersama dan anak-anaknya merasa telah mendapat traktiran istimewa dari ayahnya.
Baca juga: Jenderal Soedirman Kader Tulen Muhammadiyah
Dalam kesempatan lain, mereka pernah hanya makan nasi panas dicampur kecap, mentega, atau susu karena tak ada uang untuk beli sayur.
Kustiniyati juga menggambarkan Zainatun sebagai ibu penyabar. Pernah suatu Ketika keluarga Salim tinggal di rumah yang atapnya bocor. Bila turun hujan, air membanjiri kamar. Alih-alih panik atau sedih, Zainatun meletakkan ember untuk menampung air hujan. Ia lalu mengajak anak-anaknya membuat perahu dari kertas dan mereka asyik bermain perahu-perahuan.
Dalam buku Hadji Agus Salim: Pahlawan Nasional, Solichin Salam menulis, suatu waktu salah seorang anak Salim meninggal. Karena tak punya uang untuk membeli kafan, dia mengambil taplak meja dan kain kelambu yang sudah tak terpakai dan mencucinya untuk membungkus jenazah.
Ia menolak pemberian kafan baru dari kawannya. Agus Salim mengatakan orang yang masih hidup lebih berhak memakai kain baru itu. “Adapun yang mati, cukuplah kain itu. Selagi dia masih hidup, dia memerlukan pertolongan, akan tetapi sekarang dia tidak lagi memerlukannya.”
Haji Agus Salim bersama istrinya, Zainatun Nahar, dikaruniai delapan anak. Yaitu Theodora Atia (Dolly), Jusuf Tewfik Salim (Totok), Violet Hanifah (Jojet), Maria Zenobia (Adek), Ahmad Sjewket Salim, Islam Basari Salim, Siti Asiah (Bibsy), dan Mansur Abdur Rachman Ciddiq.
Agus Salim adalah salah satu Pahlawan Nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Perjuangannya telah dimulai sejak tahun 1910-an, dan berlangsung hingga masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949).
Karena prestasi Agus Salim di bidang diplomasi dan kefasihannya dalam berbahasa asing, julukan “The Grand Old Man” pun didapatkannya.

Perdana Menteri Natsir Jasnya Bertambal
Meski punya jabatan mentereng tapi gaya hidup Mohammad Natsirtetap bersahaja. Seperti yang dijalani oleh tokoh bangsa
Padahal dia pernah menjabat Perdana Menteri (PM) tahun 1950-1951. Dia juga pernah menjadi Menteri Penerangan tahun 1946-1947 di masa PM Sutan Syahrir dan tahun 1948-1949 saat PM dijabat Mohammad Hatta.
Menjadi pejabat negara setinggi itu tidak membuat pria kelahiran Alahan Panjang, Sumatera Barat tahun 1908, ini berubah penampilan. Rumah, pakaian, kendaraan, dan gaya hidupnya tetap bersahaja. Bahkan dia pernah terlihat memakai jas bertambal.
“Pakaiannya sungguh tidak menunjukkan ia seorang menteri dalam pemerintahan,” tulis Guru Besar Universitas Cornell, George McTurnan Kahin, dalam buku Natsir, 70 Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan.
Kahin mengaku melihat sendiri Natsir mengenakan jas bertambal. Kemejanya hanya dua setel dan sudah butut. Dia, yang mengenal sosok Natsir dari Agus Salim, mengungkapkan bahwa staf Kementerian Penerangan mengumpulkan uang untuk membelikan pakaian sang bos agar terlihat sebagai seorang menteri.
Baca juga: Presiden RI yang Terabaikan, Sjafruddin Prawiranegara
Soal kesederhanaan pakaian Natsir juga diungkapkan Yusril Ihya Mahendra yang pernah menjadi stafnya.
Menurut Yusril, saat memimpin Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) di masa Orde Baru, Natsir sering ke kantor DDII dengan pakaian yang itu-itu saja.
“Kalau tidak baju putih yang di bagian kantongnya ada noda bekas tinta, kemeja lain adalah batik berwarna biru,” kata Yusril yang pernah mendapat julukan ‘Natsir Muda’, seperti dikutip buku Natsir Politik Santun di Antara Dua Rezim, Seri Buku Tempo: Tokoh Islam di Awal Kemerdekaan (Kepustakaan Populer Gramedia, 2016).
Menolak Mobil Mewah dan Saldo
Kesederhanaan Natsir juga terlihat dari kendaraan yang dia pakai. Meski menjadi pejabat tinggi, dia hanya menggunakan mobil pribadi bermerek DeSoto yang sudah kusam.
Mobil Chevrolet Impala yang diberikan seorang tamu dari Medan dia tolak. Saat itu, tahun 1956, Natsir menjadi anggota parlemen dan memimpin Partai Masyumi.
“Mobil itu bukan hak kita. Lagi pula yang ada masih cukup,” kata Lies menirukan ucapan ayahnya ketika menolak hadiah mobil tersebut.
Padahal sedan besar buatan Amerika itu sudah terparkir di depan rumah Natsir di Jalan Jawa 28—kini Jalan HOS Cokroaminoto—Jakarta Pusat. Dan anak-anaknya terlanjur berharap mobil itu bakal jadi milik keluarga.
Baca juga: Jenderal Soedirman Kader Tulen Muhammadiyah
“Dia ingin membantu Aba karena mobil yang ada kurang memadai,” kata Sitti Muchliesah alias Lies, anak tertua Natsir pada Tempo pada 2008.
Sikap Natsir itu sesuai dengan apa yang sering dia sampaikan kepada anak-anaknya. “Cukupkan yang ada. Jangan cari yang tiada. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat,” kata Lies yang wafat 14 Maret 2010, menirukan nasihat Aba-nya, Natsir.
Kesederhanaan—juga kejujuran—Natsir terekam pula saat dia mengundurkan diri dari jabatan PM tahun 1951.
Maria Ulfa, sekretarisnya, saat itu menyodorkan sisa dana taktis. Saldonya lumayan banyak. Menurut Maria, dana itu menjadi hak perdana menteri. Tapi Natsir menggelengkan kepala. Dia menolaknya. Akhirnya dana itu dialihkan ke koperasi karyawan tanpa sepeser pun mampir ke kantong Natsir.
Bukan hanya itu. Natsir juga langsung meninggalkan mobil dinasnya di Istana Presiden, saat dia mengembalikan mandat PM. Setelah itu dia pulang berboncengan sepeda dengan sopirnya.
Natsir menolak sisa dana taknis bukan karena dia berlebih uang. Bahkan Natsir pernah tak pegang uang. Hal itu diungkapkan ‘Natsir Muda’ lainnya: Amien Rais.
Saat mahasiswa Amien mendengar cerita Khusni Muis yang pernah jadi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat.
Khusni pernah datang ke Jakarta untuk urusan partai. Saat itu Muhammadiyah adalah anggota istimewa Masyumi. Ketika hendak pulang ke Banjarmasin, dia mampir ke rumah Natsir, meminjam uang untuk ongkos pulang.
Baca juga: Diplomasi Jenaka Haji Agus Salim: Dari Jenggot hingga Pusar Adam
Tapi apa yang terjadi? Ternyata Natsir tidak punya uang karena belum gajian. Natsir akhirnya meminjam uang dari kas majalah Hikmah yang dia pimpin. “Bayangkan Perdana Menteri tidak punya uang. Kalau sekarang tidak masuk akal,” komentar Amien Rais, mantan Ketua MPR RI.
Tempat tinggal keluarga Natsir juga menjadi saksi kisah kesederhanaannya. Lies menceritakan, ketika menjadi Menteri Penerangan awal tahun 1946, keluarga Natsir tinggal seadanya di rumah Prawoto Mangkusasmito—sahabat Natsir—di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Sewaktu pusat pemerintahan pindah ke Yogyakarta, keluarganya tinggal di paviliun milik Haji Agus Salim di Jalan Gereja Theresia—sekarang Jalan H Agus Salim.
Periode menumpang di rumah orang baru berakhir ketika keluarga Natsir menempati rumah di Jalan Jawa pada akhir 1946. Rumah tanpa perabot ini dibeli pemerintah untuk rumah dinas Menteri Penerangan. “Kami mengisi rumah itu dengan perabot bekas,” kata Lies.
Ketika menjadi PM pada Agustus 1950, keluarga Natsir menempati rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat—sekarang Tugu Proklamasi. Rumah di Jalan Jawa yang sempit dan kusam dianggap tak layak untuk seorang pemimpin.
Rumah di Jalan Proklamasi ini sudah lengkap dengan perabot sehingga Natsir dan keluarga hanya membawa koper saat pindahan dari rumah di Jalan Jawa.
Pada masa ini keluarga Natsir sudah dibatasi dengan aturan protokoler. Rumah sudah dijaga polisi dan sang PM selalu didampingi pengawal. Pemerintah juga menyediakan pembantu yang membenahi rumah, tukang cuci dan masak, serta tukang kebun.
Tapi ‘fasilitas’ itu tak membuat keluarga Natsir manja. Lies yang saat itu duduk di kelas II SMP tetap naik sepeda ke sekolah karena jaraknya dekat.
Adiknya-adiknya antar-jemput dengan mobil pribadi DeSoto. Ibunya—Nur Nahar—masih melanjutkan belanja ke pasar dan kadang masak sendiri. Menurut Lies, keluarganya tidak memanfaatkan fasilitas pemerintah, misalnya perjalanan dinas.
Sebagai catatan, Lies punya lima adik, yaitu Asma Faidah, Hasnah Faizah, Aisyahtul Asriah, dan Fauzi Natsir. Sebenarnya ada lagi satu adiknya, Abu Hanifah, yang wafat saat berusia 13 tahun karena tenggelam di kolam renang.
Hidup Juga Nomaden
Pola hidup sederhana itu pula yang membuat anak-anak Natsir mampu bertahan saat suratan takdir mengubah hidup mereka: dari ‘anak Menteng’ menjadi ‘anak hutan’ di Sumatera ketika muncul Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/PRS).
Setelah periode hidup di hutan dan Natsir mendekam dari satu penjara ke penjara lain tahun 1960-1966, keluarganya kehilangan rumah di Jalan Jawa, termasuk mobil DeSoto. Harta itu diambil alih kerabat seorang pejabat pemerintah.
Saat itu keluarga Natsir menjadi ‘kontraktor’ rumah, menjalani kehidupan ‘nomaden’. Pindah dari paviliun di Jalan Surabaya sampai rumah petak di Jalan Juana, di belakang Jalan Blora, Jakarta Pusat. Rumah itu cuma terdiri atas satu kamar tidur, ruang tamu kecil, dan ruang makan merangkap dapur.
Setelah Natsir bebas dari Rumah Tahanan Militer Keagungan Jakarta tahun 1966, dia membeli rumah milik kawannya, Bahartah di Jalan Jawa 46—kini Jalan HOS Cokroaminoto—Jakarta Pusat.
Rumah itu sebenarnya dijual dengan harga teman, tapi Natsir tetap tidak mempunyai uang. Akhirnya dia harus pinjam dari sejumlah kawan dan dicicil selama bertahun-tahun.
Begitulah sekelumit episode Mohammad Natsir—bapak bangsa yang sangat sederhana menjalani hidup. Penting dijadikan teladan, kini, di tengah glamornya gaya hidup para pejabat.

Pimpin Muhammadiyah 22 Tahun Pak AR Tak Punya Rumah
Sampai wafatnya Jumat 17 Maret 1995 di usia 79 tahun, Pak AR alias K.H. Abdur Rozak Fachruddin—Ketua (Umum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah terlama (1968-1990)—tidak pernah memiliki rumah.
Rumah besar yang ditempatinya di Cik Ditiro 19A Yogyakarta sejak 1971 bukan milik pribadi melainkan milik Muhammadiyah. Sebelumnya, Pak AR sekeluarga menghuni rumah sewa sederhana di kawasan Kauman, Yogyakarta.
Mengutip merdeka.com, Pak AR sebenarnya juga ingin punya rumah sendiri. Dia pernah mengangsur rumah pada awal 1960-an ketika masih bertugas di Departemen Agama. Sayang, developer (pengembang)-nya menipu Pak AR Fachruddin. Melarikan uangnya.
Menyesal
Soal rumah yang ditipu itu Sefuddin Simon mengungkap dialog Pak AR dengan istrinya Siti Qomariyah dalam tulisan Rumah di Surga Pak AR Fachrudin yang dimuat republika.co.id.
“Pak, bagaimana perkembangan rumah kita?” kata Bu Qom—sapaan Siti Qomariyah—suatu ketika kepada Pak AR yang baru datang dari ceramah di luar kota.
Pak AR pun terdiam. Keriangan di wajahnya kelihatan pudar.
“Bu, sabar ya. Soal rumah jangan dipikirkan lagi. Developernya lari. Tak usah disesali, Allah akan mengganti rumah kita dengan rumah yang lebih baik di sorga nanti,” jawab Pak AR lirih.
Bu Qom merasa menyesal mempertanyakan soal rumah tersebut. “Saya sangat menyesal mempertanyakan rumah itu kepada Pak AR. Padahal Pak AR masih capai, baru datang dari luar kota,” kata Bu Qom menyesali munculnya pertanyaan itu.
Baca juga: Hidup Nomaden karena Tak Punya Rumah, Kesederhanaan Haji Agus Salim
Sampai bertahun-tahun kemudian, setelah Pak AR wafat, Bu Qom masih menceritakan penyesalannya soal pertanyaan rumah itu. Mungkin karena penyesalan tersebut, Bu Qom meneruskan pilihan hidup miskin tanpa memiliki rumah.
Setelah Pak AR wafat dan rumah Cik Ditiro 19A pinjaman Muhammadiyah itu diberikan kembali oleh keluarga Pak AR kepada perserikatan. Kemudian Muhammadiyah—atas usulan Prof Malik Fadjar—akan memberikan tanah seluas 1000 meter persegi dekat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk keluarga Pak AR.
Muhammadiyah juga akan membiayai pembangunan rumah keluarga Pak AR sebagai ungkapan terima kasih atas kepemimpinan Pak AR yang membesarkan Muhammadiyah selama 22 tahun.
Tapi niat baik itu ditolak secara halus oleh Bu Qom. “Tidak usahlah. Muhammadiyah lebih membutuhkan tanah itu ketimbang keluarga saya,” kata Bu AR.
‘Kontraktor’ Rumah Jin
Sebelum Pak AR tinggal di rumah pinjaman Muhammadiyah di Cik Ditiro 19A Yogyakarta, Pak AR adalah ‘kontraktor’ alias tukang kontrak rumah. Da berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Dan beberapa rumah kontrakan itu dianggap oleh orang-orang sekitar ada jinnya.
Sukriyanto AR—anak Pak AR—menceritakan, ketika bertugas di Sentolo, Kulonprogo, Pak AR menyewa rumah di selatan pasar, sebelah barat stasiun. Rumah itu sudah lama kosong, karena itu tidak ada yang berani tinggal di situ.
Pemilik rumah itu seorang janda tua yang kaya dikenal dengan panggilan Mbah Radi. Orangnya keras (galak), banyak orang yang takut padanya. Orang itu punya rumah banyak. Salah satu rumah yang katanya ditunggui “jin” itu.
Baca juga: Mohammad Natsir: Jabatan Mentereng, Gaya Hidup Bersahaja
Kata orang-orang, setiap malam di dekat sumur sering terdapat bunyi gerat-gerit, seperti orang menimba air. Karena harga sewanya murah, maka rumah itu kemudian disewa oleh Pak AR.
Dan, betul di sana memang terdapat bunyi gerat-gerit. Ketika diperhatikan bunyi itu ternyata adalah bunyi bambu yang dipakai untuk menaikkan air (Jawa: senggot), yang kalau kena angin berbunyi gerat-gerit.
Selama tinggal di situ ternyata tidak ada apa-apa, kecuali bunyi gerat-gerit itu. Jadi, lumayan dapat rumah agak luas, halamannya luas, banyak pohon mangganya, dan sewanya murah.
Jin Trowongso
Ketika pindah ke Kauman Nomor 260 BL, Pak AR tinggal—maksudnya menyewa—rumah H Abdullah. Kata orang, di rumah itu ada jin yang tinggal di situ. Namanya Trowongso. Kadang-kadang, di malam hari, sering terdengar ada suara anak menangis. Dan sering pula ada bunyi ‘dar-der’ seperti dilempari batu.
Tapi selama Pak AR tinggal di rumah itu, alhamdulillah, tidak terjadi apa-apa. Tidak pernah bertemu atau diganggu Trowongso. Memang sering terdengar seperti anak menangis, tetapi setelah diperhatikan ternyata suara binatang (sejenis luwak).
Baca juga: Presiden RI yang Terabaikan, Sjafruddin Prawiranegara
Adapun bunyi ‘dar-der’ itu setelah diperhatikan ternyata suara buah sawo yang jatuh di malam hari karena dimakan codot, jatuh di atas rumah yang kebetulan terbuat dari seng.
Saat di Semarang, Pak AR Fachruddin juga ditawari rumah yang ada jinnya. Pak AR sempat tinggal di situ sementara, tetapi karena rumahnya sangat besar dan biaya perawatannya tinggi— padahal gaji Pak AR hanya sedikit—terpaksa rumah itu ditinggalkan dan pindah ke rumah gedek (anyaman bambu) di Pindrikan, di Jalan Sadewa 45 Semarang.

Jadi Presiden, Gus Dur Tetap Sederhana
Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, dikenal sebagai sosok yang sederhana dan rendah hati. Kesederhanaan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupannya, baik dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama, tokoh masyarakat, maupun saat menjabat sebagai Presiden ke-4 Indonesia.
Sebagai sosok yang punya ‘darah biru’ dan privilege sebetulnya sangat mudah baginya untuk berlaku arogan dan hedon. Malah sebaliknya, berada di keluarga para ulama dan tokoh besar, seperti K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Wahid Hasyim, dan K.H. Bisri Sansuri, justru membuatnya semakin tawadu dan bersikap sederhana.
Ketika menjabat sebagai Presiden ke-4 RI, ada banyak kisah teladan yang terus bersambung, diabadikan lewat lisan dan tulisan, mengenai kesederhanaan dan kebijaksanaannya, dikutip dari nu.or.id.
Bercelana Pendek
Satu hal yang masih tidak pernah luput dari ingatan, terjadi pada saat pelengseran dirinya dari kursi presiden. Saat itu, ia hanya keluar dengan celana pendek menyapa para rakyatnya. Celana itu yang biasa dipakai untuk bermalam atau ketika tidak menjabat sebagai presiden. Itulah bentuk kesederhanaan yang ditampilkannya.
Saat itu, banyak orang yang mencibir apa yang dilakukan. Mereka beralasan bahwa tindakan itu tidak pantas ditampilkan seorang presiden. Bagi Gus Dur, itu tidak berlaku. Ia ingin menunjukkan dengan pakaiannya semacam itu kepada publik agar semuanya sadar bahwa presiden sama seperti manusia atau rakyat biasa, tidak ada bedanya.
Sisi lain yang tidak bisa lepas darinya ialah terbuka pada siapa saja. Tidak memandang siapa orangnya dan apa pun statusnya, Gus Dur akan tetap setia melayaninya.
Ia pernah membuat keputusan agar Istana Negara dapat terbuka untuk umum. Siapa pun boleh menginjakkan kaki, baik itu yang bersandal jepit, tak beralaskan kaki, sampai yang mengendarai bajaj pun dipersilakan mencicipi ‘kemegahan’ Istana Negara tersebut.
Ketika hadir dalam sebuah acara KBGD (Komunitas Kongkow Bareng Gus Dur) yang bisa disiarkan di radio KBR 68 H, Gus Dur tidak canggung makan gorengan, seperti bakwan, tahu, tempe dan lainnya.
Ia tidak pernah membeda-bedakan makanan. Apa yang ada di hadapannya itu yang dimakannya. (Agus Nur Cahyo, Samudra Kearifan, [Kaktus: Yogyakarta, 2018], halaman 224).
Gitu Aja kok Repot
Ada ungkapan cukup terkenal yang pernah dilontarkannya, “gitu aja kok repot”, menjadi suatu isyarat dari Gus Dur bahwa tiap persoalan yang dihadapi pasti dapat tangani dan ada jalan keluarnya. Namun, bukan berarti menggampangkan tiap permasalahan yang ada. (Subagyo, Bahasa dan Kepemimpinan: Menggali Inspirasi Discursive Leadership Soegijapranata dan Abdurrahman Wahid, [Universitas Sanata Dharma, 2012], halaman. 50-51).
Musa dalam bukunya, Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur, mengatakan jika pernyataan fenomenal itu diucapkan Gus Dur sebagai bentuk keprihatinannya terhadap urusan birokrasi yang sejatinya mudah tapi malah dipersulit. Akhirnya, sewaktu menjabat sebagai presiden, ia pun membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan yang dinilai tidak begitu berfungsi pada masa Orde Baru. Kehadirannya, justru dianggap makin mempersulit situasi yang ada. (Musa A. M, Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur, [Erlangga, 2010], halaman 23).
Tak Suka Protokoler
Selama menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia waktu itu, ia memilih menanggalkan simbol-simbol penguasa, fasilitas penguasa presiden, kawalan, dan menjaga jarak dengan publikasi di saat menghadiri acara.
Teladan kesederhanaan hidup Gus Dur memang nyata. Mengutip tulisan sebelumnya dari Muhammad Makhdum, ketika menemui seseorang yang dianggap penting, atau saat sowan kepada para kiai, bisa saja Gus Dur sebagai presiden membawa iring-iringan para pengawal, dengan bunyi sirine mobil vooridjer yang memekakkan telinga, disambut dengan upacara resmi layaknya pejabat negara.
Tapi Gus Dur malah tidak menyukai protokoler seperti itu. Bahkan, saat sowan ke ulama karismatik Mbah Abdullah Salam Kajen, Gus Dur malah datang hanya ditemani beberapa orang, dan bahkan nyelonong lewat pintu belakang pesantren, menyibak di antara pakaian yang tergantung di kawat jemuran para santri. Gus Dur juga sosok yang anti nepotisme.
Kedudukannya sebagai presiden tidak lantas dengan mudah menaikkan keluarga, kerabat, dan teman dekatnya ke panggung kursi jabatan. Tidak pernah ia memintakan jatah saham untuk dibagikan kepada anak-anaknya. Anak dan menantu justru tidak diberi penghidupan bahkan bisa disebut ‘tidak terurus’.

Buya Syafii Ikut Antre di RS Muhammadiyah
Buya Ahmad Syafii Maarif sejatinya mempunyai segala atribut untuk hidup dengan beragam fasilitas. Tapi, Ketua Umum PP Muhammadiyah 1998-2005 itu memilih jalan sunyi hidup dengan kesederhanaan.
Berikut beberapa potret kesederhanaan Buya Syafii Maarif, dikutip dari kumparan.com
Kerap Naik Sepeda
Buya Syafii yang tinggal di Yogya, dikenal gemar bersepeda baik saat mengajar maupun ke pasar. Salah satunya viral di media sosial setelah diposting Direktur Perkumpulan Masyarakat Peduli Media, Budhi Hermanto, di X.
“Saya enggak berani menyalip pengendara sepeda bertopi merah ini, ketemu di Kompleks Perumahan Nogotirto. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, berkah,” tulis Budhi.
“Ya beliau Buya Ahmad Syafii Maarif,” imbuhnya.
Naik Kereta
Buya bagi orang di sekelilingnya juga dikenal sebagai sosok yang ‘tak ingin merepotkan orang lain’. Di antara momen itu terjadi pada 12 Agustus 2017 saat Buya memilih naik KRL dari Tebet menuju Bogor.
Kisah itu diceritakan mantan Direktur Eksekutif Maarif Institute, Abdullah Darraz. Buya sempat mengabari Darraz saat akan ke Jakarta untuk menghadiri peluncuran program BPIP.
“Direktur, sy otw Kby Lama, tomorrow to Bogor by KRL. Maarif”, bunyi pesan singkat Buya kepada Darraz.
Darraz menyebut di Maarif Institute selalu siap kendaraan yang ada untuk mengantar-jemput Buya selama beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya. Namun, kata Darraz, sering kali orang tua yang satu ini dalam beberapa hal, terutama dalam kesahajaan dan kesederhanaannya sangat konservatif dan terlalu ekstrem.
“Saya sudah sediain mobil di kantor, cuma kalau Sabtu-Minggu sering anggap anak Maarif libur, enggak mau ngeberatin,” ucapnya.
Foto Buya saat menunggu kereta di Stasiun Tebet, juga saat berada di dalam kereta viral di Twitter.
Antre di Rumah Sakit
Potret kesederhanaan lain Buya adalah karena tak ingin diistimewakan. Buya pernah kedapatan antre di rumah sakit Muhammadiyah saat check-up.
Dikutip dari suaramuhammadiyah.id, Buya yang saat itu berusia 83 tahun memilih antre untuk check-up, meski dia sangat mungkin untuk diberikan akses tanpa antrean. Terlebih rumah sakit yang didatangi adalah RS milik organisasi yang pernah Buya pimpin.
“Anda kembali saja ke kantor, Anda bekerja saja, tidak perlu menemani nunggu antrean ini,” kata Buya kepada Pemimpin Perusahaan Suara Muhammadiyah, Deni Asy’ari, yang ikut menemani Buya di RS.
Selain tiga kisah itu, Buya pernah juga terekam saat makan di angkringan, membeli sabun cucian di warung, berangkat ke acara seminar dengan mengayuh sepeda, potong rambut di tukang cukur biasa, dan lainnya.

Haedar Nashir Bawa Kardus di Stasiun
Meski menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memiliki aset triliunan rupiah, gaya hidup Haedar Nashir tetap bersahaja. Dia pernah tertangkap kamera saat bepergian menggunakan kereta api. Dia sendirian, tanpa disertai rombongan, apalagi pengawal.
Dalam foto yang beredar luas di media sosial, Haedar Nashir terlihat sedang di ruang tunggu di Stasiun Kereta Api Kediri.
Menurut akun X @Muhammadiyah momen itu terjadi di Stasiun Kediri saat Haedar hendak Kembali ke Yogyakarta selepas menghadiri peresmian gedung SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo dan Gedung Rawat Inap RS Ahmad Dahlan Muhammadiyah Kediri
Berkemeja batik dengan warna kombinasi ungu, hijau, dan biru; bercelana warna biru, berkaca mata baca; dan kepala tanpa peci apalagi surban, Haedar tampak asyik membuka handphone-nya. Penampilannya tak menampakkan bahwa dia seorang kiai atau ajengan dan salah tokoh penting Indonesia yang mendapat julukan sang Muazin Bangsa.
Seperti kebanyakan warga masyarakat yang sedang berpergian jauh, di samping tempat duduk Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu terdapat rangsel dan beberapa tas jinjing. Dan yang mengejutkan ada kardus oleh-oleh bertuliskan ‘Pers. Tahu dan Takwa’. Semua dia bawa sendiri.
Jumatan di Teras Masjid
Haedar Nashir juga pernah tertangkap kamera saat sedang mendengarkan khotbah Jumat di teras terluar masjid. Karena masjid sudah penuh, maka Haedar hanya kebagian sedikit tempat duduk saat khotbah Jumat, namun hal itu tidak menjadi soal.
“Pak Dr Haedar Nashir kemarin dari Jogja ke Semarang naik mobil untuk menghadiri sidang terbuka doktor Ketum Dahnil Anzar (mantan Ketum Pemuda Muhammadiyah),” kata Wazhirman, salah satu alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mengomentari peristiwa ini, dikutip dari muhamamdiyagl.com.
Pada tahun 2016, Yusuf Mansur melalui akun instagram memposting sebuah foto bersama Haedar Nashir. Dalam postingan tersebut, dia menuliskan kesannya:
“Saya belajar minimal 2 hal dari Prof Haedar Nashir, Pimpinan Umum Muhammadiyah. Saya yang muda, malah disamperin. Belajar ketawadhuan. Dari bawah, dari bandara, bareng. Beliau menyalami duluan saya. Padahal beliau Ketua Umum organisasi BUESAR BUANGET. Papasan. Saya mau keluar mushalla. Beliau mau ke arah mushalla. Saya tungguin beliau. Bareng.
Sampe pesawat, karena beda beberapa seat, misah. Tapi setelah kondisi boleh wara wiri dan lepas sabuk pengaman, saya malah keduluan. Beliau nyamperin saya. Subhaanallaah. Akhlak pemimpin. Saya kudu belajar banyak. Ga usah malu nyamperin. Daripada telat, keburu disamperin.” (#)
Mohammad Nurfatoni, dari berbagi sumber